Menghindari Ghibah, Mempererat Ukhuwah

Laduni.ID, Jakarta - Sering kita melihat di sekitar atau bahkan di medsos, antara sesama muslim terkadang masih saling menggunjing, memfitnah, menghina, mengejek, mencibir, mencemooh, menghujat, mengumpat, mencaci maki, membuka aib seseorang, mencari kesalahan orang lain dan lainnya. Semua hal itu dapat menjadikan seseorang tersakiti. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara tegas melarang dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12:
یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱجۡتَنِبُوا۟ كَثِیرࣰا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمࣱۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا یَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَیُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن یَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِیهِ مَیۡتࣰا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابࣱ رَّحِیمࣱ
"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Masuk dengan GoogleDan dapatkan fitur-fitur menarik lainnya.
Support kami dengan berbelanja di sini:
.png)

 Rp57.500
Rp57.500
 Rp467.100
Rp467.100
 Rp209.930
Rp209.930
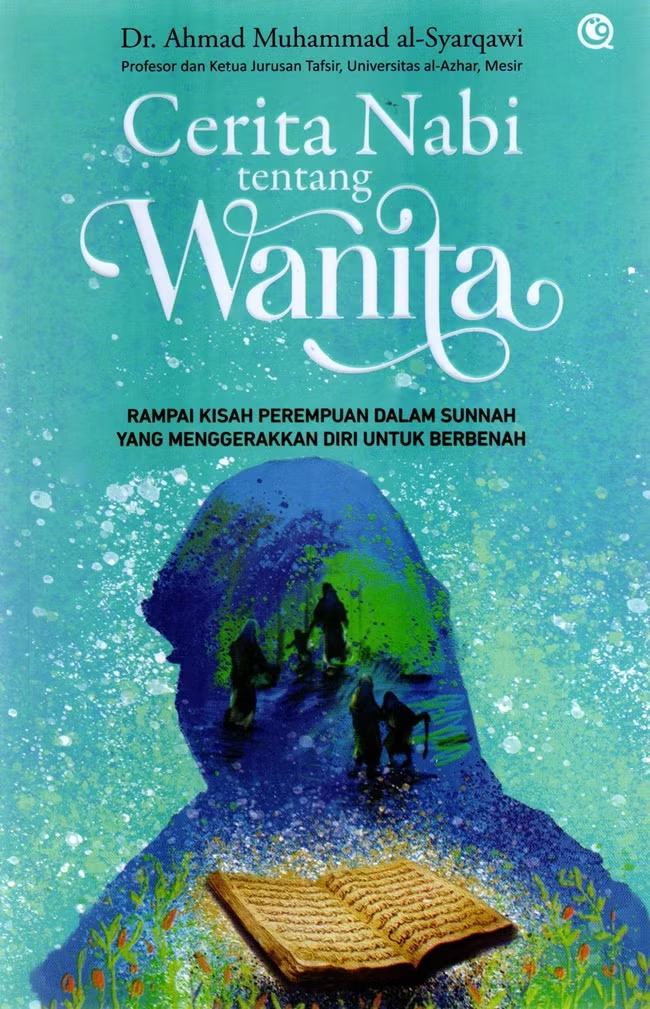 Rp85.000
Rp85.000














Memuat Komentar ...