Ini Penjelasan Tauhid Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani

LADUNI.ID, Jakarta - Kendati Syekh Abdul Qadir al-Jailani menggambarkan ihwal Hadarah al-Quds sebagai maqam tertinggi salik yang telah bermakrifatulLah, beliau qaddasahulLah dengan penuh arif bijaksana terus mendorongkan harapan besar kepada kita untuk bisa menggapai maqam ahli tauhid itu. Seberat dan sepelik apa jalan menujunya. Yakni melalui penekanannya yang sangat ketatterhadap kepatuhan syariat sesuai ajaran Allah Swt dan RasulNya. Inilah jalan terang yang terdekat dengan pemahaman kita: bahwa tiada taqarrub ilalLah, apalagi hakikat dan makrifat, tanpa fondasi amal syariat yang teguh….
Jika kita rujukkan kembali kepada tulisan sebelumnya tentang hierarki ilmu, kita perlu mengingat dua jenjang syariat ini:
Pertama, menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya sebagai kesadaran dan pengakuan diri atas penghambaan kita kepada Allah Swt.
Kedua, memahami dengan semakin detail dan utuh dari masa ke masa tujuan-tujuan yang menjadi arah bagi lelaku pertama tadi. Apa gerangan hikmah di balik kita menjalankan dengan taat kewajiban shalat dan puasa, misal? Apa gerangan hikmah di balik kita bersungguh-sungguh dalam menjauhi maksiat-maksiat yang dibenci oleh Allah Swt? Serta, yang mesti kemudian kita arungi, apa dampaknya (seperti atsar al-shalat, bekas shalat) kepada hidup kita di dunia ini, kepada sesama manusia, bahkan kepada alam sekitar kita?
Syariat kiranya adalah perpaduan antara bukti nyata kepatuhan kita kepada ajaran Allah Swt dan RasulNya, di satu sisi. Ketika misal Allah Swt memerintah kita untuk berdoa, maka berdoalah –kendati kita tahu dan iman betul bahwa Allah Swt Maha Mengetahui apa saja yang terbetik di dalam hati.
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:

 Rp479.000
Rp479.000
 Rp179.000
Rp179.000
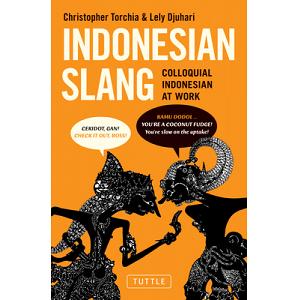 Rp259.000
Rp259.000
 Rp299.000
Rp299.000











Memuat Komentar ...