Robohnya Ramadhan Kami

LADUNI.ID - Ramadhan kali ini tercoreng oleh aksi kerusuhan dan kekerasan massa yang memicu jatuhnya korban jiwa. Spiritualitas Ramadhan sebagai bulan penuh berkah dan ampunan Tuhan yang semestinya memancarkan aura kekhusyukan dan kekhidmatan beribadah ternyata tidak mampu meredam anarki dan amuk massa dari sejumlah pihak yang menolak hasil pemilu.
Akibatnya, sakralitas Ramadhan dikotori oleh profanitas hasrat politik-kekuasaan yang telah menempatkan ideologi menang-kalah sebagai persoalan hidup-mati.
Persoalannya, mekanisme hukum yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa pemilu telanjur dianggap oleh pihak tertentu sebagai bagian dari political gimmick semata. Akibatnya, wacana people power untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dipercaya sebagai satu- satunya jalan menumbangkan kebatilan dan kezaliman penguasa.
Namun, apa pun alasannya, anarkisme dan kerusuhan massa yang dapat mengganggu ketertiban umum harus ditindak tegas dalam bingkai penegakan hukum (law enforcement) yang adil, beradab, dan manusiawi.
Agitasi dan provokasi
Awalnya adalah ketidakdewasaan sejumlah elite dalam menyikapi hasil kontestasi politik. Patut disayangkan, sejumlah elite justru menjadi pemantik—secara langsung ataupun tidak langsung—bagi meletusnya aksi kerusuhan. Alih-alih menyuarakan keteduhan dan kedamaian, sejumlah elite justru memperkeruh suasana dengan serangkaian lontaran- lontaran kalimat yang provokatif dan agitatif melalui media sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kematangan dan kedewasaan berdemokrasi di kalangan elite kita masih jauh panggang dari api.
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:

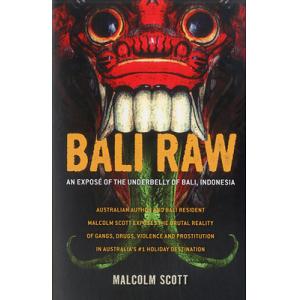 Rp298.000
Rp298.000
 Rp149.000
Rp149.000
 Rp100.000
Rp100.000
 Rp114.000
Rp114.000





(1).jpg)








Memuat Komentar ...