Menyoal "Kedekatan" Ulama dengan Penguasa

Laduni.ID, Jakarta - Merebak sebuah paham di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini tentang dua kategori ulama. Kategori yang pertama adalah ulama yang memilih penguasa, sedangkan yang kedua adalah penguasa yang memilih ulama. Kategori pertama adalah jenis yang menunjukkan tingginya peran seorang ulama sehingga dia memutuskan siapa yang hendak dituntunnya sebagai penguasa, dalam konteks yang lebih riil sebagai presiden. Sedangkan tipe kedua, ulama yang dipilih oleh penguasa untuk berada di sisinya. Dalam narasinya, diangkatlah jenis ulama yang pertama ini sebagai sebenar-benarnya ulama, sedangkan yang kedua sebagai ulama yang buruk (Al-Ulama’ As-Su’), ulama bayaran atau istilah-istilah lainnya.
Klasifikasi di atas memang penuh problem, hal ini karena pengelompokan yang seperti ini seringkali mereduksi banyak hal, termasuk pemahaman masyarakat umum terhadap sosok ulama yang akan mereka teladani. Karena, harus kita akui bahwa peran ulama di kancah politik di Indonesia akhir-akhir ini memang sedang begitu tingginya. Dalam babakan sejarah demokrasi Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa peran ulama sebegitu diperhitungkan, suara politik umat Islam begitu diperhatikan, sehingga seperti sebuah syarat kalau ingin menang, maka suara umat Islam harus diamankan. Karena memang penduduk terbesar di Indonesia adalah masyarakat Muslim.
Problem masyarakat awam (terutama yang ngamuk'an), dengan gampang sekali disulam untuk menjadi “mangsa” utama krisis pemahaman ini. Dengan gampang mereka menerima bahwa ulama yang “benar-benar ulama” adalah mereka yang bersikap kritis pada pemerintahan. Sedangkan, ulama yang berada pada pihak penguasa saat ini akan diklaim sebagai penjilat belaka.
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Masuk dengan GoogleDan dapatkan fitur-fitur menarik lainnya.
Support kami dengan berbelanja di sini:
.png)

 Rp175.000
Rp175.000
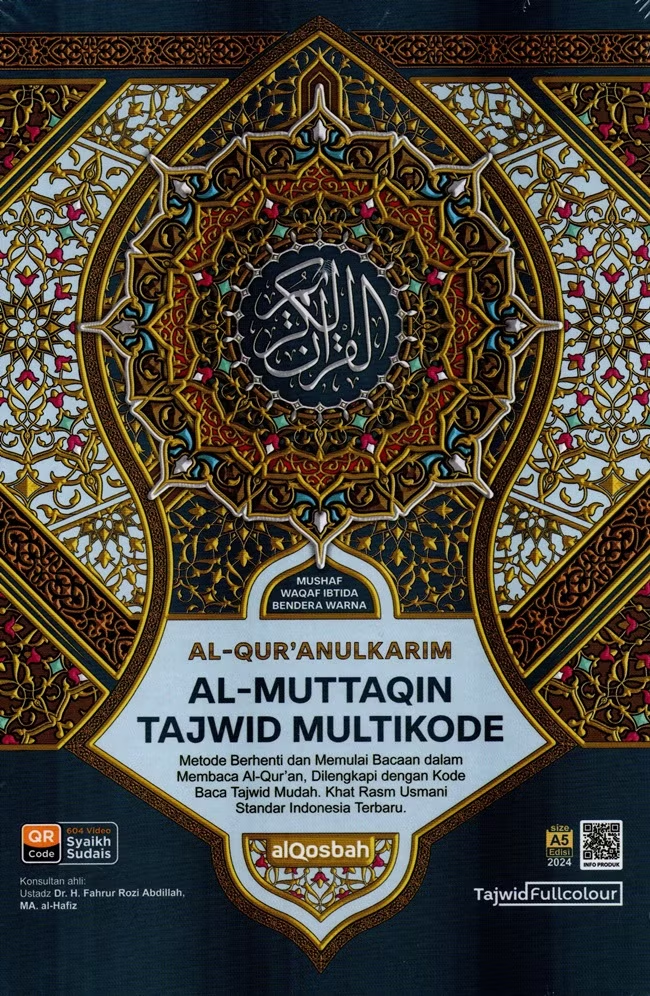 Rp65.000
Rp65.000
 Rp65.000
Rp65.000
 Rp90.100
Rp90.100












Memuat Komentar ...