Bolehkah Seorang Istri Mengambil Uang Suami Tanpa Izin?

LADUNI.ID, Jakarta - Memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban utama bagi seorang suami. Nafkah yang dimaksud tidak hanya kebutuhan lahiriah, namun juga kebutuhan batiniah. Selain memenuhi kebutuhan istri, seorang suami juga wajib menafkahi anaknya sampai mereka dewasa dan bisa mandiri. Kedua hal ini sudah menjadi tanggung jawab suami dan konsekuensi sebagai kepala rumah tangga.
Perjalanan mahligai rumah tangga tentu tidak selamanya berjalan mulus. Sesekali mungkin akan ada rintangan dan cobaan yang menyebabkan suami jengkel, istri merajuk, dan anak yang nakal. Semua cobaan ini hendaknya perlu dihadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Salah satu masalah rumah tangga yang seringkali dihadapi adalah masalah nafkah. Kaum wanita (istri) berada di garda depan untuk membela urusan nafkah tersebut karena terkadang mereka sering ditelantarkan. Nafkahnya kurang, dan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Ketika istri berada dalam posisi tersebut, seorang istri terpaksa harus mengambil uang suami tanpa izin darinya. Ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan lahiriahnya.
Lalu bagaimana Hukum Istri Mengambil Uang Suami Tanpa Izin darinya?
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Masuk dengan GoogleDan dapatkan fitur-fitur menarik lainnya.
Support kami dengan berbelanja di sini:
.png)

 Rp135.000
Rp135.000
 Rp62.500
Rp62.500
 Rp79.000
Rp79.000
 Rp23.940
Rp23.940




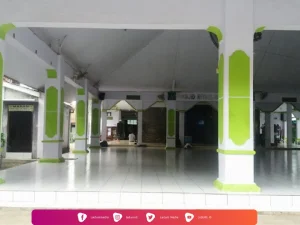








Memuat Komentar ...