Sabili Sang Majalah Jurnalisme Berdarah

LADUNI. ID, KOLOM- Akhir 1999, di tembok musala terminal (lama) Ponorogo, tertempel selebaran-selebaran ajakan jihad ke Ambon. Saya membaca, darah berdesir, panas. "Saudara-saudara kita dibantai orang Kresten, kang." kata seseorang di samping saya yang ikut membaca pamflet merah dengan font mencolok dan kalimat bombastis itu.
Seiring dengan banyaknya poster dan selebaran ajakan berjihad, Majalah Sabili menemukan momentumnya. Takdir menghampirinya. Tirasnya melejit. Laris manis bak permen Milkita.
Saya mulai membaca Sabili, majalah "islam" terlaris saat itu. Isinya wakwau...top! Provokatif dan disertai istilah-istilah yang baru bagi saya: Salibis, Sepilis, Perang Salib, Konspirasi, Kuffar, Antek Zionis, Agen Yahudi, penjual Islam, de el el. Inilah majalah yang diolah menggunakan jurnalisme pamflet: desain menarik dan diselingi kalimat meledak-ledak.
Saya sering membeli Sabili di toko buku La Tansa milik Pondok Gontor itu. Di kemudian hari, saya yang masih langsing (!), dipinjami salah satu guru saya yang berlangganan majalah yang sering memakai sampul warna hitam dengan desain keren itu. Sejak saat itu saya rajin mengkonsumsi Sabili 3 kali sehari (uhuk) di kamar. Teman-teman sepondok nggak ada yang minat sama majalah ini. Maklum, sahabat saya lebih asyik hafalan nadzom. Sedangkan saya asyik tiduran hahaha
Hingga tiba saat bapak--saya memanggilnya abi-- jauh-jauh datang dari Jember menyambangi saya, akhir 2000. Bapak melirik bertumpuk-tumpuk majalah Sabili yang ada di lantai.
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:

 Rp359.000
Rp359.000
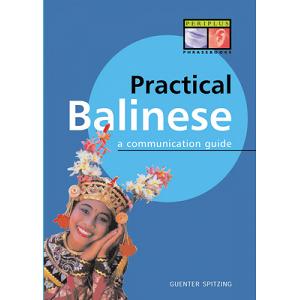 Rp78.000
Rp78.000
 Rp94.000
Rp94.000
 Rp198.000
Rp198.000












Memuat Komentar ...