Kisah Sendu Pentalqin Mayat di Era Digital

LADUNI.ID, Jakarta - "Buk, tolong ibu saya. Tolong talkinkan ibu saya. Tolong ...," pinta Ipung, anak tetanggaku. Wajah memelas dalam nafas terengah-engah. Mungkin untuk menuju kemari, ia harus berlari-lari.
Aku kaget bukan kepalang mendengar ucapan Ipung. Memang Bu Min, ibunya Ipung, sudah sakit sejak lama. Penyakit diabetes yang dideritanya terus menggerogoti daya tahan tubuh. Terakhir kali, beliau sudah tidak bisa berjalan. Jika kebetulan lewat dan melihatnya terduduk di kursi roda di teras rumah, biasanya aku akan menyapa dan bercengkrama sebentar. Bahkan, tadi pagi pun, sepulang belanja sayur, aku masih menyapanya. Tak dinyana, sore hari harus mendengar kabar ini.
"Inna lillahi ... oh iya, Pung. Hayuk. Eh, bentar dulu," tukasku. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumah. Menyimpan sendok nasi yang masih tergenggam di tangan. Tadi, gedoran keras dari luar membuatku terburu-buru membuka pintu.
Tanpa sempat berganti baju, aku dan Ipung berjalan cepat menuju rumah Bu Min.
Di komplek ini, entah apa alasannya, aku sudah beberapa kali dipanggil untuk menalkinkan orang. Profesi? Bukan. Mengiyakan permintaan bantuan para tetangga untuk menalkinkan orang dalam kondisi darurat seperti itu, banyak pelajaran yang bisa kudapat.
Meski, seringkali ada tanya yang menghampiri, "Bagaimana kelak kondisiku saat di situasi seperti itu? Adakah yang bersedia membimbingku? Apakah aku bisa lolos dalam ujian itu?"
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:

 Rp50.000
Rp50.000
 Rp256.000
Rp256.000
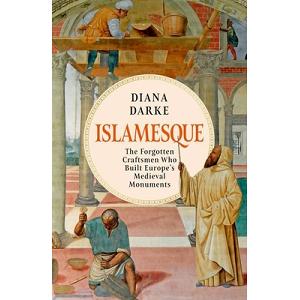 Rp635.000
Rp635.000
 Rp894.000
Rp894.000













Memuat Komentar ...