Kemaksiatan atau Vulgar

LADUNI.ID | Kolom --
Foto ini konon diambil di sebuah jalan di Vancouver, Kanada. Saya comot dari sebuah grup senirupa. Aslinya tidak seperti itu. Suasana sebelah menyebelahnya sengaja saya kaburkan. Supaya fokus kepada karya seni jalanan ini. Terutama kepada pesan yang saya duga ingin disampaikan senimannya. Agar tak terganggu oleh lainnya.
Dan ketika saya sodorkan kepada sejumlah teman, berbuihlah kami tentangnya. Ada yang ngilmiah milosofis dengan mengaitkannya pada isu gender dan feminisme, dengan menyebut-nyebut "upaya sia-sia menghapus masoginis".
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Masuk dengan GoogleDan dapatkan fitur-fitur menarik lainnya.
Support kami dengan berbelanja di sini:
.png)

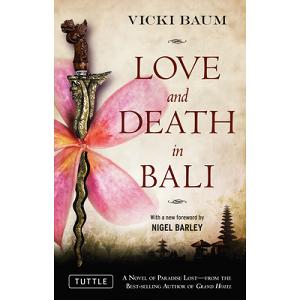 Rp288.000
Rp288.000
 Rp180.000
Rp180.000
 Rp368.750
Rp368.750
 Rp260.000
Rp260.000












Memuat Komentar ...