Barikan Sebagai Penangkal Bencana yang Sudah Menjadi Tradisi di Nusantara

Hubungan masyarakat dengan alam di sekelilingnya merupakan wujud kesatuan harmonis yang selalu dijaga keseimbangannya. Kejadian-kejadian alam seperti gempa, gerhana bulan dan matahari, paceklik, banjir, wabah penyakit dianggap sebagai pertanda bagi kehidupan manusia. Dengan adanya pertanda baik atau pertanda buruk, diharapkan masyarakat telah bersiap untuk menghadapinya dari segala kemungkinan atas petunjuk alam itu. Untuk menghindari hal-hal tersebut, seluruh anggota masyarakat suatu desa mengadakan upacara barikan. Tradisi barikan atau bari’an merupakan salah satu praktik ritual keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat atau berkah yang telah mereka terima dari sang Kuasa.
Barikan atau bari’an sendiri berasal dari kata bahasa Arab baro’a, yubarri’u, bara’atan/ bari’an yang berarti bebas (al-Marbawi, t.th: 45). Dalam hal ini yang dimaksud dengan bebas adalah bebas dari barbagai marabahaya, wabah penyakit, malapetaka, marabahaya, dan balak yang ada. Istilah lain dari ritual barikan juga seringkali disebut sebagai ritual “bersih desa” (Simuh, 1998: 119). Sedangkan secara terminologi, barikan adalah sebuah ritual tradisi Jawa yang dilakukan suatu penduduk desa sebagai bentuk upaya melakukan tolak balak (menghindarkan berbagai mara bahaya), agar hidup mereka terhindar dari berbagai bencana yang merugikan seperti datangnya kekeringan, bencana alam (banjir, longsor), kelaparan, wabah penyakit baik yang menyangkut manusia, tanaman ataupun ternak mereka (Soepanto, 1981: 23).
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:

 Rp53.100
Rp53.100
 Rp0
Rp0
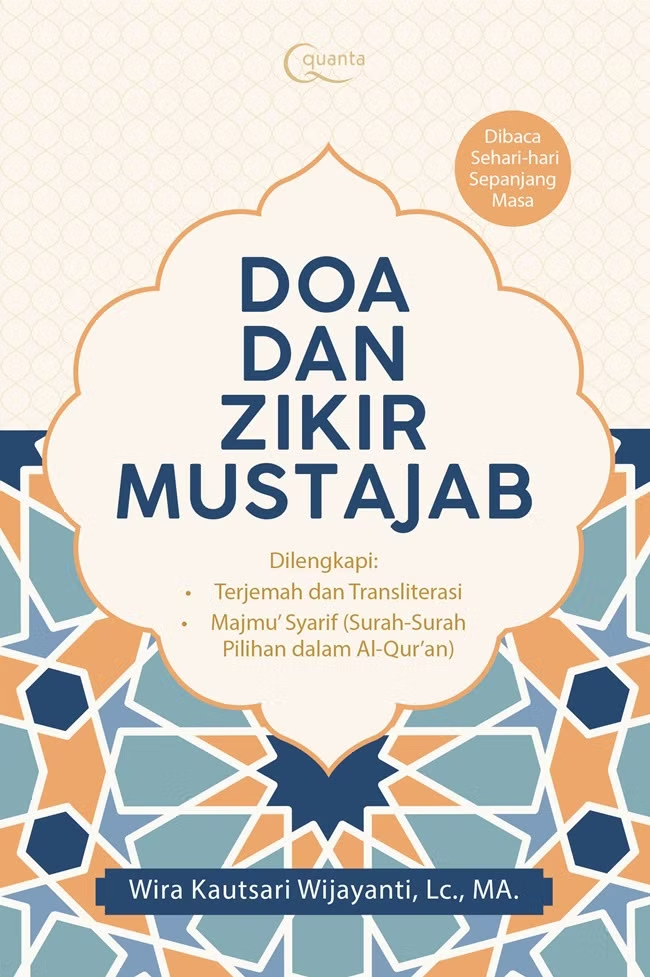 Rp76.000
Rp76.000
 Rp137.000
Rp137.000












Memuat Komentar ...