Merasa Benar Sendiri, Pangkal Islam yang Tertinggal

LADUNI.ID, Jakarta - Di media sosial kian bertebaran ujaran-ujaran kebencian: gara-gara beda pandangan keagamaan dengan sangat mudah seorang ulama dikatai munafik, bahkan seringkali lebih kasar daripada itu. Padahal sama-sama islamnya. Ya, suasana sosial-agama kita-Indonesia-saat ini memang sedang tegang. Mulai dari makian, sampai tindakan ekstrim pun siap dilakukan cukup dengan alasan “beda pandangan”.
Ada yang mengaitkan semua ini dengan masalah politik praktis. Bisa betul, bisa juga salah. Tetapi menurut saya isu politik hanya sekadar “angin lalu” yang bisa datang dan pergi kapan saja.
Ada yang lebih mendasar dari itu. Barangkali yang menjadikan kita saat ini mudah disorong kesana kemari dan “digoreng” dengan isu-isu yang sekedar angin itu adalah karena nihilnya prinsip nalar-kritis dalam masyarakat kita. Ditambah model beragama yang sedang tren saat ini. Banyak dari mereka yang terlalu empirik dalam beragama dan cenderung simbolik- dan puncak dari empirisme adalah egoisme dan mendahulukan pendapat sendiri, yang dalam berbagai kesempatan kita lihat digunakan untuk menyalahkan yang berbeda.
Imbasnya, kini orang-orang tak lagi mengenal tradisi dialog yang arif, dan semakin menjauh dari apa yang kita sebut dengan toleransi. Pada akhirnya perbedaan tak berarti lagi: yang tak sependapat dengan pandangannya harus salah, kalau perlu digali makamnya, atau dimunafik-munafikkan, bahkan dikafir-kafirkan.
Kita tak perlu menyebutkan semua masalah satu persatu. Kita cukup merasakannya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Islam yang begitu agung dan luasnya, bahkan menjadi mayoritas dalam negara kita Indonesia, faktanya begitu terasing dan dibuat sekat-sekat oleh apa yang disebut dengan “perbedaan”. Entah kenapa saya berpikir bahwa apa yang dipanjanglebarkan Syakib Arslan (1869-1946) ternyata benar. Dalam bukunya
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:
.png)

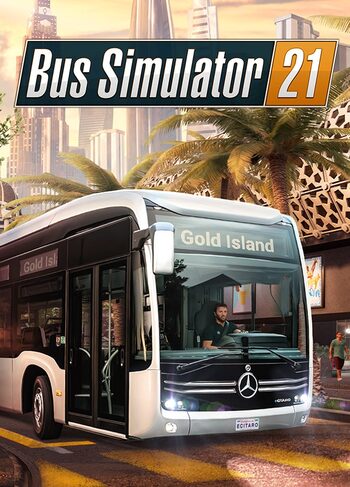 Rp250.353
Rp250.353
 Rp135.000
Rp135.000
 Rp27.500
Rp27.500
 Rp79.900
Rp79.900














Memuat Komentar ...