Apakah Nama dan Sifat yang Disandarkan pada Allah SWT Sesuai Ajaran-Nya?
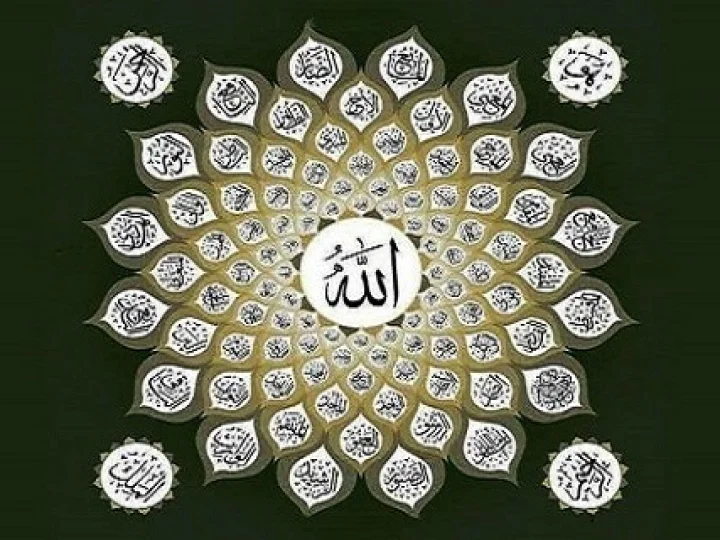
LADUNI.ID, Jakarta – Apakah nama-nama dan sifat-sifat yang diterapkan pada Allah Swt. didasarkan pada ajaran Allah[1] atau dibolehkan berdasarkan akal?
Yang lebih disukai Qadhi Abubakar[2] adalah mengizinkan digunakannya akal kecuali di mana wahyu melarangnya atau di mana pengertian suatu ungkapan akan mengandung sesuatu yang mustahil bagi Allah Swt. Adapun apa yang tidak mengandung unsur yang melarang, maka dibolehkan. Namun Al-Asy’ari[3] berpendapat bahwa itu didasarkan pada ajaran Allah, sehingga tidak dibolehxan menerapkan pada Allah Ta’ala apa pun yang bersandar pada makna-makna yang dinisbahkan kepada-Nya, kecuali bila disahkan. Adapun kami, posisi yang kami anggap lebih baik adalah mengenali dan mengatakan: apa pun yang bertalian dengan nama-nama maka itu didasarkan pada otorisasi, sedangkan apa pun yang bertalian dengan sifat-sifat maka itu tidak didasarkan pada otorisasi. Namun yang otentik dapat diterima, sedangkan yang palsu tidak. Ini tidak akan dimengerti sebelum dipahami perbedaan antara nama dan sifat.
Kami katakan bahwa nama adalah ucapan yang dilakukan untuk menunjukkan sesuatu yang dinamai.[4] Ambil contoh Zayd. Namanya adalah Zayd, namun sesungguhnya dia itu rupawan dan tinggi. Nah jika seseorang mengatakan kepadanya: ‘Wahai tinggi! Wahai rupawan! maka dia memanggilnya dengan apa yang dinisbahkan kepadanya dan ini benar. Namun itu akan terlebih dahulu menggunakan namanya, karena namanya adalah Zayd dan bukan yang tinggi dan juga bukan yang rupawan.[5] Karena tinggi dan rupawan artinya bukanlah bahwa ‘tinggi’ adalah namanya. Kalau kita menamai seorang anak lelaki dengan nama Qasim atau Jami’, maka ini tidaklah berarti bahwa dia dapat digambarkan dengan makna dari nama-nama ini.[6] Tetapi namanama ini, sekalipun bila nama-nama ini kebetulan mengandung suatu makna, hanyalah menunjukkan seperti yang ditunjukkan Zayd, ‘Isa dan nama-nama lain yang tidak membawa makna sama sekali.[7] Meskipun kita menamakan dia ‘Abd Al-Malik, yang kita maksud bukanlah [193] bahwa dia adalah hamba raja. Dan karena itulah kita perlakukan ‘Abd Al-Malik sebagai satu istilah tunggal, seperti ‘Isa dan Zayd, sedangkan jika digunakan sebagai gambaran maka itu akan merupakan suatu istilah ga bungan. Begitu pula dengan ‘Abdullah (hamba Allah), di mana kita membentuk jamaknya dengan sebuah kata ’Abadila bukannya dengan dua kata ‘Ibad Allah.[8]
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Masuk dengan GoogleDan dapatkan fitur-fitur menarik lainnya.
Support kami dengan berbelanja di sini:
.png)

 Rp198.000
Rp198.000
 Rp256.000
Rp256.000
 Rp98.600
Rp98.600
 Rp179.000
Rp179.000



.jpg?p=small)




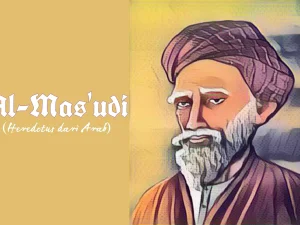


.jpg?p=small)
Memuat Komentar ...