Melacak Kembali Jejaring Ulama Diponegoro (Bagian 2)

Laduni.ID, Jakarta – Setidaknya ada tiga hal yang bisa dicatat sebagai kunci keberhasilan Pangeran Diponegoro mengobarkan Perang Jawa dan kaitannya dengan konteks gerakan kekinian. Kunci-kunci ini penting untuk dipelajari mengingat perang yang berlangsung sejak 1825-1830 Masehi (M) ini merupakan perlawanan terbesar masyarakat Jawa yang amat merepotkan dan menguras kas penguasa kolonial Belanda. Dari sesama anak bangsa pun Pangeran Diponegoro harus berhadapan dengan keraton-keraton yang telah dikuasai penjajah.
Pertama, jejaring ulama santri yang sejak lama dibangun dan dibina Pangeran Diponegoro sehingga dukungan meluas di tanah Jawa. Bahasan ini bahkan menjadi perhatian utama penulis yang mengurai secara rinci hingga jejaring itu terbentuk, baik karena garis keturunan, hubungan guru murid (sanad keilmuan), hubungan menantu, maupun perjuangan. Termasuk jaringan dengan Turki Utsmani yang dapat dilacak dari taktik perjuangan dan penamaan laskar.
Jejaring santri ini pula yang terus bergerak meski karena pengkhianatan tokoh utama akhirnya ditangkap dan dibuang ke Makassar. Bahkan keluarga, para pendukung, santri, panglima perang yang menghindari kejaran Belanda pasca penangkapan kemudian menyebar dan mengubah strategi perjuangan dengan mendirikan pesantren-pesantren untuk mencetak kader-kader penerus.
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:
.png)

 Rp59.000
Rp59.000
 Rp93.200
Rp93.200
 Rp600.000
Rp600.000
 Rp144.636
Rp144.636








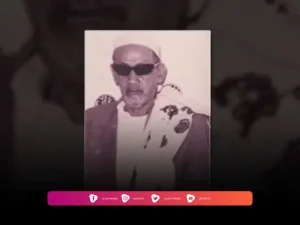



Memuat Komentar ...