Kolom Gus Nadir: Intermezzo, Benarkah Punya Istri Cantik itu Syarat Menjadi Imam Shalat?

LADUNI.ID - Dalam sebuah perjalanan ke Tunisia tahun 1991 saya ikut mendampingi Abah saya bersama rombongan ulama dari tanah air. Diskusi dengan para ulama Tunisia kerapkali diselingi berbagai guyonan. Salah satunya mengenai syarat menjadi imam Shalat.
Abah saya berkisah di depan para hadirin: “Dulu Bapak saya, KH Hosen, bercerita bahwa siapa yang lebih layak menjadi Imam Shalat. Kedua orang yang hendak shalat ini ternyata sama-sama memenuhi kriteria sesuai berbagai riwayat hadits Nabi:
—bagus tilawahnya dan banyak hafalan Qur’annya.
—wara’
— lebih awal masuk Islam
— mengerti fiqh
Selain sama-sama memenuhi kriteria di atas, ternyata usia mereka berdua juga sebaya, dan tidak ada yang lebih tua. Keduanya juga sudah sama-sama menikah. Tidak ada yang statusnya sebagai musafir atau budak. Maka untuk menyelesaikan perdebatan ini, lantas Bapak saya menyodorkan kriteria terakhir, yaitu: siapa yang paling cantik istrinya?!”
Para ulama yang mendengar kisah tersebut langsung tertawa. Ada yang nyeletuk: “Wah semakin susah ini: masing-masing akan mengklaim istrinya-lah yang paling cantik.”
Ada yang memberi komentar lebih serius: “Masuk akal kriteria terakhir itu. Siapa yang istrinya lebih cantik, maka dia akan lebih terjaga pandangan matanya. Sehingga dia lebih layak jadi imam Shalat.”
Hari ini entah kenapa saya terkenang dialog tersebut. Mungkin karena kangen guyonan sambil diskusi dengan almarhum Abah saya. Saya jadi penasaran ingin tahu sumber rujukan kriteria terakhir, “siapa yang lebih cantik istrinya?’ itu. Adakah kitab-kitab fiqh membahasnya.
UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN
Support kami dengan berbelanja di sini:
.png)

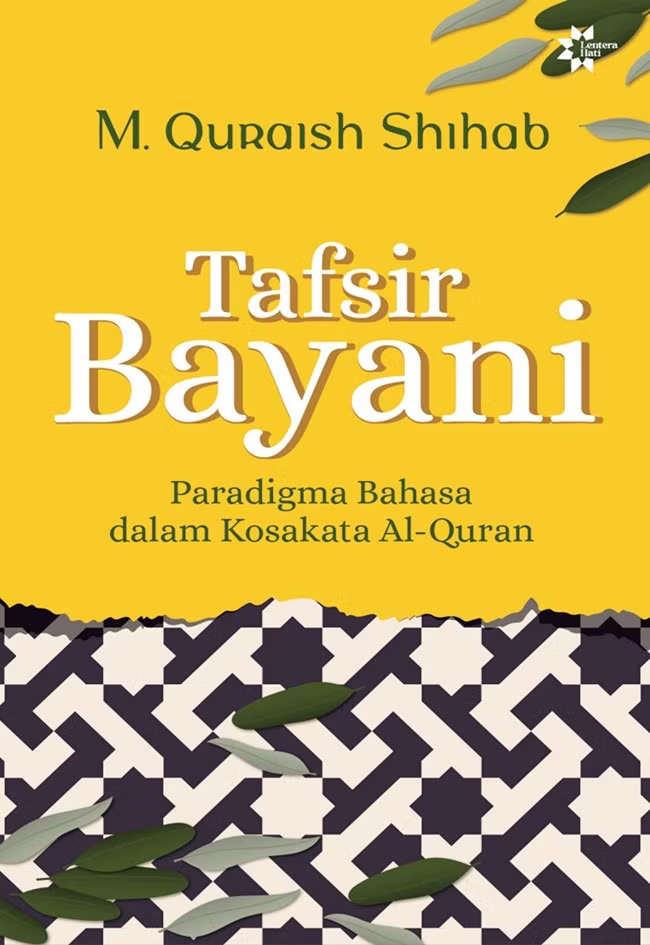 Rp125.000
Rp125.000
 Rp189.000
Rp189.000
 Rp598.000
Rp598.000
 Rp695.000
Rp695.000













Memuat Komentar ...